Materi IPS Kelas 7 | Semester
Ganjil
PERTEMUAN 1
Materi Kelas 7 | Semester Ganjil
BAB I
MANUSIA, TEMPAT DAN LINGKUNGAN
A. Pengertian Ruang dan Interaksi Antarruang
- Saling Melengkapi (Complementarity
atau Regional Complementarity)
- Persebaran Penduduk
B. Letak
dan Luas Indonesia
- Pemahaman Lokasi Melalui Peta
- Letak dan Luas Indonesia
C.
Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia
- Potensi Sumber Daya Alam
Indonesia
- Potensi Kemaritiman Indonesia
D.
Dinamika Kependudukan Indonesia
- Jumlah Penduduk
- Persebaran Penduduk
- Komposisi Penduduk
- Pertumbuhan dan Kualitas
Penduduk
- Keragaman Etnik dan Budaya
- E. Kondisi Alam Indonesia
- Keadaan Fisik Wilayah
- Flora dan Fauna
F.
Perubahan Akibat Interaksi Antarruang
- Berkembangnya Pusat-pusat
pertumbuhan
- Perubahan Penggunaan Lahan
- Perubahan Orientasi Mata
Pencaharian
- Berkembangnya Sarana dan
Prasarana
- Adanya Perubahan Sosial dan
Budaya
- Berubahnya Komposisi Penduduk
BAB II INTERAKSI
SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL
A. Interaksi Sosial
- Pengertian dan Syarat Interaksi
Sosial
- Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
B. Pengaruh Interaksi
Sosial Terhadap Pembentukan Lembaga Sosial
C. Lembaga Sosial
- Pengertian Lembaga Sosial
- Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial
PERTEMUAN 2
BAB I MANUSIA, TEMPAT DAN LINGKUNGAN
A. Pengertian Ruang dan Interaksi Antarruang
Peta Konsep
PERTEMUAN 3
Pengertian
ruang
1.
Ruang adalah tempat di
permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan
oleh makhluk hidup untuk tinggal.
Kata ‘Ruang’ mencakup:
ü
Udara yang bersentuhan dengan
permukaan bumi,
ü
Atmosfer terbawah yang
memengaruhi permukaan bumi,
ü
Perairan yang ada di permukaan
bumi (laut, sungai, dan danau) dan di bawah permukaan bumi (air tanah) sampai
kedalaman tertentu,
ü
Lapisan tanah dan batuan
sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan,
ü
Berbagai organisme atau makhluk
hidup juga merupakan bagian dari ruang.
Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan
unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi.
2.
Interaksi adalah suatu proses
yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik
melalui kontak langsung atau tidak langsung.
Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang
datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara
misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi dan lain-lain.
Interaksi antarruang terjadi akibat perbedaan karakteristik
ruang-ruang tersebut.
Ada beberapa kondisi saling
bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu:
- saling
melengkapi (complementarity atau Regional Complementarity),
Contohnya interaksi antara penduduk di wilayah pegunungan dengan
penduduk di wilayah pesirir. Penduduk di Wilayah pegunungan menghasilkan
sayuran, sementara penduduk di wilayah pesisir menghasilkan ikan.
Penduduk di pegunungan membutuhkan ikan, dan penduduk di pesisir
membutuhkan sayuran, maka hal ini akan mendorong terjadinya interaksi
keruangan.
- kesempatan
antara (intervening opportunity),
Contohnya interaksi antara Wilayah A yang membeli ikan dari
Wilayah B, namun kemudian diketahui bahwa Wilayah C yang jaraknya lebih dekat
menjual ikan dengan harga murah. Keadaan seperti ini mendorong Wilayah A
berinteraksi dengan wilayah C.
- keadaan
dapat diserahkan/dipindahkan (transferability)
contohnya interaksi antar wilayah A dan
Wilayah B harus melalui jalan rusak, sementara Wilayah A ke Wilayah C dengan
melalui jalan mulus. Maka interaksi antara wilayah A dan Wilayah C akan menjadi
dominan, karena kemudahan transfer, kemudahan memindahkan barang, dan ongkos yang dikeluarkan lebih murah serta waktu lebih
singkat.
Persebaran Penduduk
PERTEMUAN 4
B.
Letak dan Luas
Indonesia
- Pemahaman Lokasi Melalui Peta
Lokasi
suatu tempat dapat dilihat melaui peta. Zaman sekarang ini penampil peta bisa
berupa buku atlas, maupun halaman website seperti google.maps atau bing.maps
maupun yang lainnya.
Peta
adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan
menggunakan skala.
Agar dapat membaca peta,
diperlukan memahami hal-hal sebagai berikut:
a.
Judul Peta; yang menunjukkan isi
suatu peta
b.
Skala Peta; yang menunjukkan
perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan.
Contoh, skala peta: 1 : 1.000.000 (1 cm : 1.000.000 cm | 1 cm sama dengan 1
km).
Skala ada dua macam, yaitu skala angka dan skala garis atau
grafis
c.
Orientasi utara; yang ditunjukan
dengan symbol berbentuk panah.
d.
Simbol peta; yaitu tanda khusus
yang ada pada peta mewakili objek yang dipetakan agar memudahkan pengguna.
Simbol-simbol yang biasa digunakan:
Simbol titik, dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga,
dan lainnya.
Simbol garis
Simbol warna
Simbol area
e.
Garis koordinat; yang merupakan
garis khayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur.
f.
Inset; yaitu peta kecil yang ada
pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang lebih luas.
g.
Legenda; yang menunjukkan
keterangan semua objek yang ada atau muncul pada peta.
h.
Sumber peta; yang menunjukkan
orang atau lembaga yang membuat peta.
PERTEMUAN 5
- Letak dan Luas Indonesia
Letak
lokasi suatu wilayah disajikan melalui dua cara, yaitu (1) letak geografis dan
(2) letak Astronomis.
Letak Astronomis Indonesia
Letak
astronomis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari posisi
kordinatnya.
Letak
astronomis Indonesia terletak antara 95OBT – 141 dan 6OLU
– 11OLS
Perhatikan Posisi Indonesia. Daerah yang ditandai arsiran merupakan wilayah tropis.
Letak Geografis Indonesia.
Letak
Indonesia secara geografis berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu
benua Asia dan Benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Batas
wilayah Indonesia
Utara : Benua Asia
Selatan : Benua
Australia
Barat : Samudra
Hindia
Timur : Samudra
Pasifik
Negara
tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia ada 10, yaitu:
Batas laut : India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,
Palau, PNG, Australia dan Timur-Leste.
Batas darat : Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan
Timor Leste.
Keuntungan
dari posisi tersebut adalah Indonesia menjadi sangat strategis sebagai negara
yang menjadi lajur lalu lintas perdagangan dunia.
Luas wilayah Indonesia
Wilayah
Indonesia terdiri dari lautan dan daratan. Daratan Indonesia seluas 1.922.570
km2 dan perairan seluas 3.257.483 km2
Keuntungan
posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada
jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan
Lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api.
Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber
energi dan mineral.
PERTEMUAN 6
C.
Potensi Sumber
Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia
Sumber daya alam adalah semua bahan yang
ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan
tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup.
Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat
dalam beragam bentuk, diantaranya adalah air, tanah, udara, batuan, hutan,
bahan tambang, dan lain-lain.
1.
Potensi sumber daya alam Indonesia
Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat
dalam beragam bentuk, diantaranya adalah air, tanah, udara, batuan, hutan,
bahan tambang, dan lain-lain.
-
Sumber daya alam hutan, dikenal
oleh penduduk adalah sebagai sumber kayu. Secara umum, jenis-jenis kayu dan
sebarannya adalah sebagai berikut:
1).
Keruing, meranti, dan agathis, è dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan.
2).
Kayu jati, è dari Jawa Tengah
3).
Rotan è dari Kalimantan, Sumatra
Utara dan Sumatra Barat.
4).
Kayu cendana è dari Nusa Tenggara
Timur.
5).
Kayu rasamala dan akasia è dari Jawa Barat.
Selain menghasilkan kayu, hutan juga mempunyai
manfaat dan fungsi sebagai berikut:
1).
Menyimpan air hujan dan kemudian
mengalirkannya ke sungai
2).
Tempat hidup berbagai jenis flora
dan fauna
3).
Mencegah erosi atau pengikisan
tanah
4).
Menghasilkan oksigen, menyerap
karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali.
5).
Sumber kehidupan bagi masyarakat
sekitar.
2.
Potensi sumber daya tambang
1).
Minyak bumi dan gas
2).
Batu Bara
3).
Bauksit
4).
Pasir Besi
5).
Emas
Di bawah ini adalah peta persebaran hasil tambang
Persebaran Daerah Penghasil Minyak Bumi, di sajikan
pada tabel berikut:
3.
Potensi Kemaritiman Indonesia
-
Perikanan
-
Hutan mangrove
- Terumbu karang
PERTEMUAN 7
D. Dinamika Kependudukan Indonesia
1.
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Indonesia
mencapai 256 Juta Jiwa (Word Population Data Sheet –WPDS; 2015)
Jumlah penduduk di suatu daerah/wilayah/negara
akan mengalami perubahan dengan 3 sebab, yaitu: 1) Kelahiran [natalitas], 2) Kematian [mortalitas], dan 3) Perpindahan
[migrasi].
Peringkat Jumlah Penduduk
|
Peringkat |
Nama Negara |
Jumlah Pendudduk (Juta Jiwa) |
|
1 |
Cina |
1.372 |
|
2 |
India |
1.314 |
|
3 |
Amerika
Serikat1 |
321 |
|
4 |
Indonesia |
256 |
2.
Persebaran Penduduk (Distribusi
Penduduk)
Persebaran
atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah
atau negara, apakah merata atau tidak.
Persebaran
dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan merupakan indikator adanya
perbedaan sumber daya, dengan persepsi bahwa wilayah dengan sumber daya yang
baik, cenderung dipadati penduduk.
3. Komposisi
Penduduk
Komposisi
penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasakan usia, umur, jenis kelamin,
mata pencaharian, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dll.
a.
Komposisi Penduduk berdasarkan
usia disajikan sebagai berikut:
|
No. |
Usia Penduduk |
Jumlah Penduduk |
|
1. |
0-5 |
|
|
2. |
6-10 |
|
|
3. |
10-15 |
|
|
4. |
16-20 |
|
|
5. |
21-25 |
|
|
6. |
26-30 |
|
|
7. |
31-35 |
|
|
8. |
36-40 |
|
|
9. |
41-45 |
|
|
10. |
46-50 |
|
|
11. |
51-55 |
|
|
12. |
56-60 |
|
|
13. |
61-65 |
|
|
14. |
<65 |
|
cara
lain penyajian adalah:
|
%
(persen |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
87,5 |
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
62,5 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
37,5 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
12,5 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< 15 |
15 - 65 |
>
65 |
b.
Komposisi penduduk berdasarkan perbandingan
jenis kelamin (sex ratio) dapat
digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk yang berkenaan
dengan pekerjaan, tanggung jawab, pendidikan dan lain sebagainya.
PERTEMUAN 8
4.
Pertumbuhan dan Kualitas Penduduk
Pertumbuhan
penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan
yang mengurangi jumlah penduduk.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk:
-
Kelahiran
-
Kematian
-
Migrasi (perpindahan penduduk)
baik masuk (Imigrasi) yang menyebabkan penambahan penduduk maupun keluar
(Emigrasi) yang menyebabkan pengurangan penduduk.
Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan hal-hal
berikut:
a.
Pertumbuhan penduduk usia muda
bisa menjadi sebab tingginya angka pengangguran.
b.
Persebaran penduduk tidak merata.
c.
Beban ketergantungan tingga
karena banyak penduduk usia muda.
d.
Kualitas dan tingkat
kesejahteraan penduduk menurun.
5.
Keragaman Etnik dan Budaya
a.
Rumah Adat
|
Nama Daerah |
Nama Rumah Adat |
|
Nangroe Aceh Darussalam |
Krong Bade |
|
Yogyakarta |
Rumah Joglo |
|
Sumatra Barat |
Rumah Gadang |
|
Bali |
Rumah adat Gapura Candi Bentar |
|
Papua |
Rumah adat Honai |
|
Sulawesi Utara |
Rumah adat Istana Buton |
|
Kalimantan Timur |
Rumah adat Lamin |
|
Kalimantan Selatan |
Banjar atau Betang |
|
Nusa Tenggara Timur |
Musalaki |
|
Kalimantan Tengah |
Betang |
|
Papua |
Honai |
b.
Pakaian Adat
1.
Ulee balang: pakaian adat Aceh.
2.
Bundo kanduang: pakaian adat
Sumatra Barat.
3.
Ulos: pakaian adat Sumatra Utara.
4.
Aesan gede: pakaian adat Sumatra
Selatan.
5.
Teluk belanga: pakaian adat
Kepulauan Riau.
6.
Pakaian adat melayu: pakaian adat
Riau.
7.
Melayu Jambi: pakaian adat Jambi.
8.
Paksian: pakaian adat Bangka
Belitung.
9.
Melayu Bengkulu: pakaian adat
Sumatra Selatan.
10.
Tulang bawang: pakaian adat
Lampung.
11.
Pangsi: pakaian adat Banten.
12.
Pakaian adat Betawi: pakaian adat
DKI Jakarta.
13.
Kebaya Sunda: pakaian adat Jawa
Barat.
14.
Kesatrian ageng: pakaian adat
Daerah Istimewa Yogyakarta.
15.
Kebaya Jawa: pakaian adat Jawa
Tengah.
16.
Pesa'an: pakaian adat Jawa Timur.
17.
Safari dan kebaya: pakaian adat
Bali.
18.
Pakaian adat suku sasak: pakaian
adat Nusa Tenggara Barat.
19.
Pakaian adat NTT: pakaian adat
Nusa Tenggara Timur.
20.
King bibinge dan king baba:
pakaian adat Kalimantan Barat.
21.
Upak nyamu: pakaian adat
Kalimantan Tengah.
22.
Ta'a dan sapei sapaq: pakaian
adat Kalimantan Utara.
23.
Bagajah gamuling baular lulut:
pakaian adat Kalimantan Selatan.
24.
Kustin: pakaian adat Kalimantan
Timur.
25.
Lipa saqbe mandar: pakaian adat
Sulawesi Barat.
26.
Nggembe: pakaian adat Sulawesi
Tengah.
27.
Laku tepu: pakaian adat Sulawesi
Utara.
28.
Kinawo: pakaian adat Sulawesi
Tenggara.
29.
Bodo: pakaian adat Sulawesi
Selatan.
30.
Biliu dan makuta: pakaian adat
Gorontalo.
31.
Cele: pakaian adat Maluku.
32.
Manteren lamo: pakaian adat
Maluku Utara.
33.
Ewer: pakaian adat Papua Barat.
34.
Koteka: pakaian adat Papua.
c.
Tarian Daerah
|
No. |
Nama Tarian |
Asal Daerah |
|
1. |
Tari Seudati |
Aceh |
|
2. |
Tari Legong |
Bali |
|
3. |
Tari Jaipong |
Jawa Barat (Karawang) |
|
4. |
Tari Cokek |
DKI Jakarta (Betawi) |
|
5. |
Tari Piring |
Minangkabau |
<<Untuk lebih lengkap daftar nama
tarian daerah silahkan cari sendiri
Di sini juga ada:
https://ipsku-duridwangurunatafkar.blogspot.com/2022/09/tarian-daerah-di-indonesia-dan-asalnya.html>>
PERTEMUAN 9
E.
Kondisi Alam Indonesia
1.
Keadaan Fisik Wilayah
Keadaan
fisik suatu wilayah dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan
iklim.
a.
Kondisi Geologis
Indonesia terletak pada pertemuan tiga
lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng
pasifik.
Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan
lempeng Eurasia di lepas pantai sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara. Lempeng
Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan
lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi
gunung api di sepanjang pulau Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara.
Gunung berapi adalah lubang kepundan atau
rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan
lainnya ke permukaan bumi.
Perhatikan Gambar peta berikut ini:
PERTEMUAN 10
b.
Bentuk muka bumi
Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan
menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan.
Seperti tampak pada peta fisiografi sebagai
berikut:
c.
Kondisi Iklim Indonesia
Indonesia berada di wilayah tropis. Adapun ciri iklim
tropis adalah suhu udara di sepanjang tahun yaitu sekitar 27oC. Di
daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan
dan musim kemarau.
Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh
tiga jenis iklim yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis.
·
Iklim muson. Periode perubahan adalah setiap
enam bulan
·
Iklim tropis. Suhu yang tinggi
mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan.
·
Iklim laut. Penguapan yang
terjadi akibat udara melintasi laut yang luas, sehingga akhirnya mengakibatkan
hujan.
Menurut
perhitungan kalender, musim hujan di Indonesia terjadi pada kisaran bulan
Oktober sampai April. Peristiwa ini terjadi akibat angina muson dari Samudra
Pasifik menuju Indonesia, dibelokan oleh gaya coriolis sehingga berubah arah
menjadi angina barat yang membawa banyak uap air. Sehingga turun hujan di
Indonesia.
Sebaliknya
pada kisaran bulan Mei sampai September, angina muson dari Benua Australia
(angina muson timur) bergerak menuju benua Asia yang bertiup melalui lautan
sempit sehingga uap air yang dikandungnya sedikit sehingga terjadilah musim
kemarau.
Pada
musim hujan, para petani siap-siap bercocok tanam, dan pada musim kemarau sebagian
petani terpaksa membiarkan lahannya karena pasokan air berkurang. Sementara
sebagian yang lain masih bisa mengandalkan air sungai dan aliran irigasi.
Sebaliknya
nelayan pada musim hujan, justru mengurangi frekuensi melaut untuk menghindari
cuaca buruk, dan pada musim kemarau nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa
banyak terganggu oleh cuaca buruk.
PERTEMUAN 11
2.
Flora dan Fauna
Indonesia
memilik keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman
hayati Indonesia termasuk tiga besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di
Amerika Selatan dan Zaire di Afrika.
Berdasarkan
data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999 jumlah spesies
tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies, dan 2.215 spesies hewan yang terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1519
burung, dan 121 kupu-kupu.
a.
Persebaran flora di Indonesia
Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:
1)
Flora Indo-Malayan, meliputi
tumbuhan kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatra, Kalimantan, Jawa dan Bali.
2)
Flora Indo-Australian, meliputi
tumbuhan kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua.
Perhatikan karakteristik Flora Indonesia di bawah ini:
Adapun pemanfaatan flora Indonesi berupa kayu atau
rotan adalah untuk bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan dan bahan
lainnya.
b.
Persebaran fauna di Indonesia
Fauna di Indonesia dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu (1)
bagian barat, (2) bagian tengah dan (3) bagian timur.
Garis pemisah antara bagian barat dengan bagian tengah adalah
garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah
dengan bagian timur adalah Garis Weber.
Tipe fauna di bagian barat disebut tipe asiatis, sementara tipe
fauna di bagian timur disebut tipe asutralis. Adapun fauna bagian tengah
merupakan fauna peralihan yang memilik tipe berbeda pula dengan 2 tipe
sebelumnya.
Adapun hewan-hewan utama di masing-masing bagian adalah sebagai
berikut:
1)
Fauna bagian barat, yaitu gajah,
harimau, badak cula satu dan banteng
2)
Fauna bagian tengah, yaitu anoa,
komodo, kuskus, dan babi rusa.
3)
Fauna bagian timur, yaitu walabi
(kangguru kecil), landak irian, cendrawasih dan Nuri.
PERTEMUAN 11
F.
Perubahan Akibat Interaksi Antarruang
Interaksi antarruang dapat terjadi dalam
berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan dan informasi.
Pergerakan tersebut menimbulkan perubahan.
Berbagai akibat yang ditimbulkan dari interaksi keruangan ini diantaranya
adalah:
1.
Berkembangnya Pusat-pusat
pertumbuhan
Pergerakan orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu
akan menimbulkan pemusatan aktifitas manusia pada lokasi tujuan.
2.
Perubahan Penggunaan Lahan
Aktifitas penduduk yang terus meningkat memerlukan lahan utnuk
menampung aktifitas tersebut.
3.
Perubahan Orientasi Mata
Pencaharian
Kebutuhan terhadap barang dan jasa menuntuk manusia untuk
bekerja. Perubahan ruang, atau pengalihan fungsi lahan mendorong sebagian
manusia untuk merubah orientasi pekerjaan sesuai ketersedian sarana dan
prasarana yang ada.
Misalnya para petani yang lahan sawah dan kebunnya dijadikan
pemukiman atau lahan industri, dari pekerjaan bertani menjadi karyawan pabrik.
Demikian juga sebaliknya.
4.
Berkembangnya Sarana dan
Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya pergerakan orang,
barang atau informasi diantaranya adalah kendaraan, jalan, fasilitas umu,
pusat-pusat perdagangan, dan lain sebagainya.
5.
Adanya Perubahan Sosial dan
Budaya
Pergerakan manusia akan disertai dengan interaksi sosial, dalam
interaksi sosial terjadi pengaruh dan mempengaruhi. Hal ini bisa saja terjadi
pada aspek sosial seperti nilai dan norma masyarakat, dan juga terjadi pada
aspek budaya.
Misalnya gaya akademisi timur tengah yang bergamis ditiru oleh
guru-guru di Indonesia.
6.
Berubahnya Komposisi Penduduk
Interaksi keruangan yang tak mengenal status sosial, etnis dan
suku bangsa, bisa mengakibatkan perubahan komposisi penduduk yang awalnya
seragam menjadi beragam.
PERTEMUAN 12
BAB II
INTERAKSI SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL
PERTEMUAN 13
A. Interaksi Sosial
1.
Pengertian dan Syarat Interaksi
Sosial
a.
Pengertian interaksi sosial
Interaksi sosial adalah
hubungan-hubungan antara orang perorang, antar kelompok, maupun antara orang
perorangan dengan kelompok manusia.
Berlangsungnya suatu proses
interaksi sosial didasarkan atas beberapa hal, diantaranya:
1)
Faktor imitasi yaitu proses
mencontoh orang lain atau kelompok
2)
Faktor sugesti yaitu proses gerak
tubuh yang timbul dari pengaruh getaran hati orang.
3)
Faktor Identifikasi yaitu
kecendrungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain.
4)
Faktor simpati yang merupakan
kemampuan untuk meraskaan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut
merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain.
b.
Syarat-syarat
Syarat terjadinya interaksi adalah 2 hal, yaitu:
1) Kontak
2) Komunikasi
c.
Ciri-ciri interaksi
Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial
apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya dua atau lebih.
2) Berlangsung secara timbal balik
3) Adanya komunikasi antar pelaku dengan symbol-simbol yang
disepakati
4) Adanya suatu tujuan tertentu.
PERTEMUAN 14
2.
Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
Beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat,
yaitu sebagai berikut:
a.
Interaksi asosiatif
Interaksi asosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada
kesatuan pandangan. Dalam interaksi ini bisa terjadi 3 hal berikut, yaitu (1)
kerjasama (2) akomodasi (3) asimilasi.
1)
Kerjasama
Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara
orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan
bersama.
Dalam pelaksanaan kerjasama, ada lima bentuk aktifitas, yaitu:
·
Kerukunan,
·
Bargaining (tawar menawar) dalam pekerjaan
dengan mempertimbangkan sudut pandang, kebutuhan, keinginan, ketakutan, dan
perhatian pihak lain.
·
Kooptasi
·
Koalisi, dan
·
Joint venture yaitu suatu bisnis atau usaha
yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam periode waktu tertentu
sesuai kesepakatan
Pelaku
kerjasama di masyarakat bisa datang baik dari warga sekitar, teman bermain,
teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya.
2)
Akomodasi
Akomodasi adalah suatu proses interaksi yang menunjukan pada
usaha-usaha untuk meredakan suatu pertentangan, untuk mencapai kestabilan.
Akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa
menghancurkan lawan sehingga lawan tidak hilang kepribadiannya.
3)
Asimilasi
Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam
menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan.
Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa
cara, diantaranya: sikap toleransi, sikap menghargai orang dan kebudayaannya,
dan perkawinan campuran.
PERTEMUAN 15
b.
Interaksi disosiatif
Interaksi disosiatif adalah interaksi yang mengarah pada
perpecahan, konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri
atas tiga bentuk, yaitu (1) kompetisi (2) kontravensi (3) pertentangan.
1)
Kompetisi (persaingan)
Kompetisi adalah suatu proses
individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui
bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah
piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan
yang lainnya.
Jenis persaingan ada dua, yaitu
persaingan individu dan persaingan kelompok.
Dalam kehidupan nyata, persaingan
bisa terjadi berupa persaingan ekonomi, persaingan budaya, persaingan kedudukan
dan jabatan, dsb.
2)
Kontravensi
Kontravensi adalah sikap mental
tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu
golongan tertentu. Contohnya OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi
kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut. Rasa kurang setuju berkembang
menjadi tidak suka bahkan benci. Namun karena disembunyikan tidak sampai
menjadi pertentangan dan pertikaian.
3)
Pertentangan (konflik)
Pertentangan adalah suatu proses
dimana individu atau kelompok berusaha utnuk memenuhi tujuannya dengan jalan
menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan.
Konfik bisa terjadi jika dua
pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing masing.
Penyebab terjadinya konflik bisa
berasal dari perbedaan antar individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan
dan perubahan sosial.
Bentuk-bentuk konflik,
diantaranya:
·
Konflik pribadi,
·
Konflik sosial,
·
Konflik politik, dsb.
Akibat-akibat yang bisa
ditimbulkan dari terjadinya konflik adalah:
·
Harta benda hancur,
·
Kebahagiaan keluarga terampas,
·
Nyawa banyak orang bisa
terenggut.
PERTEMUAN 16
B.
Pengaruh
Interaksi Sosial Terhadap Pembentukan Lembaga Sosial
Interaksi
sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial
tidak mungkin ada kehidupan bersama.
Bertemunya
orang perorangan menghasilkan suatu kelompok yang kemudian membutuhkan suatu
aturan, maka lahirlah lembaga.
Manusia
mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosial muncul bisa menjadi
saluran pemenuh kebutuhan tersebut. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan,
maka lembaga berupa sekolah bisa menjadi saluran pemenuh kebutuhan tersebut.
Dalam
kehidupan lembaga sekolah, terjadi interaksi sebagai berikut:
-
Orang tua mendaftakan anaknya
-
Anak-anak yang didaftarkan bertemu dan
berinteraksi
-
Lembaga sekolah penerima, menerapkan aturan dan
tata tertib
Contoh lain
adalah kebutuhan ekonomi. Orang-orang mencari kebutuhan baik berupa barang atas
jasa, para penyedia barang atau jasa seperti pedagang berkumpul, terbentuklah
pasar, dan terjadilah interaksi jual beli.
Interaksi
sosial berpengaruh terhadap lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan.
Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati,
hidup rukun dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan
keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan mendorong munculnya
lembaga sosial.
PERTEMUAN 17
C.
Lembaga Sosial
1.
Pengertian Lembaga Sosial
Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang
terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga
dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan
dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat.
Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah
laku. Norma memberi tahu kalau perilaku kita itu salah atau benar.
<<Pada awalnya norma-norma
tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun,
lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Missalnya dalam bidang
ekonomi, dahulu seorang perantara tidak harus diberi bagian. Namun perubahan
terjadi, seorang perantara lama-kelamaan harus diberi bagian baik oleh penjual
maupun oleh pembeli.>>
<<Contoh lain, tata tertib
di sekolah. Pada zaman dahulu peserta didik tidak harus menggunakan pakaian
seragam, namun kemudian dengan berjalannya waktu dan kepentingan menjaga
ketertiban, pakaian seragam harus dikenakan oleh peserta didik.>>
Sistem norma atau aturan-aturan
yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut.
b. Norma tersebut menjiwai seluruh warga masyarakat dalam sistem
sosial.
c. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota
masyarakat.
Di dalam masyarakat dikenal ada empat tingkatan
norma, yaitu sebagai berikut:
a. Cara (usage)
b. Kebiasaan (folksway)
c. Tata kelakuan (mores)
d. Adat istiadat (customs)
Adapun pengertian keempat norma
tersebut adalah sebagai berikut:
|
No. |
Nama Norma |
Pengertian |
|
1 |
Cara (usage) |
Norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang
ringan terhadap pelanggarnya. |
|
2 |
Kebiasaan (folksway) |
Norma yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang
sama. |
|
3 |
Tata kelakuan (mores) |
Kebiasaan yang tidak hanya dianggap tidak hanya sebagai
perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur |
|
4 |
Adat istiadat (customs) |
Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku
masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi
keras akan didapatkan dari masyarakat. |
Lembaga sosial umumnya lahir
berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial,
masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi
perilaku manusia dalam kehidupan bersama.
Contoh penerapan norma.
|
No. |
Nama Norma |
Pengertian |
Sanksi |
|
1 |
Cara (usage) |
Berbicara kepada orang yang lebih tua dengan berteriak |
Ditegur |
|
2 |
Kebiasaan (folksway) |
|
|
|
3 |
Tata kelakuan (mores) |
|
|
|
4 |
Adat istiadat (customs) |
|
|
PERTEMUAN 18
Lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama.
2.
Fungsi lembaga sosial
Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai
jenis lembaga sosial, dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling
melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Secara umum, lembaga sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
1)
Memberikan pedoman pada
anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah
laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan
sekitar.
2)
Menjaga keutuhan masyarakat yang
bersangkutan.
3)
Memberikan pedoman kepada
masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (kontrol sosial).
3.
Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial
a.
Jenis dan macam-macam lembaga
sosial
Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya
bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan
lembaga politik.
1)
Lembaga keluarga
Keluarga merupakan unit sosial
terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya.
Keluarga berperan membina dan
membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun
lingkungan budaya dimana ia berada.
Keluarga terbentuk dari sebuah
perkawinan. Dalam keluarga hubungan antar anggota keluarga diatur sehingga
setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas.
Contohnya sebagai berikut:
-
Ayah berperan sebagai kepala
keluarga yang sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap
keluarganya.
-
Ibu berperan sebagai pengatur,
pengurus, dan pendidik anak-anaknya;
-
Seorang anak harus membantu kedua
orang tuanya.
PERTEMUAN 19
Pada umumnya, lembaga keluarga memilik fungsi sebagai
berikut:
a)
Fungsi reproduksi, artinya
keluarga yang dibangun dari sebuah perkawinan diharapkan akan memberikan
keturunan.
b)
Fungsi proteksi (perlindungan),
artinya keluarga memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarganya
sehingga tercipta rasa aman. Dengan rasa aman di keluarga, maka proses-proses
sosial dapat berjalan harmonis.
c)
Fungsi ekonomi, artinya keluarga
yang dibangun menjalankan roda perekonomian karena manusia adalah (homo
economicus) yaitu makhluk ekonomi. Dalam keluarga, idealnya ayah bekerja, ibu
mengelola, dan anak-anak terpenuhi kebutuhannya dalam menjalani hidup belajar
dan menambah wawasan menghadapi kehidupan dimasa depan sebagai generasi penerus
perjuangan hidup orang tuanya.
d)
Fungsi sosialisasi, artinya
keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang
tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak. Kemudian
anak dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup dengan orang lain di lingkungan
yang lebih luas.
e)
Fungsi afeksi, artinya keluarga
memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya tanpa
membeda-bedakan.
f)
Fungsi pengawasan sosial, artinya
keluarga yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai anggotanya,
masing-masing kepada satu sama lain saling memberikan kontrol dan saling
mengawasi sesuai usia dan proporsinya. Namun kenyataannya bahwa fungsi ini
biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya.
g)
Fungsi pemberian status, artinya
keluarga yang dibangun dari mulai awal menikah, maka seseorang mendapatkan
status atau kedudukan baru di masyarakat sebagai suami, atau sebagai istri.
Status suami sebagai pemimpin dan pelindung bagi istrinya dan status istri
sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Setelah
mereka memperoleh keturunan, mereka mendapat status sebagai ayah dan ibu.
Keturunannya berstatus sebagai anak. Status keluarga setelah mendapatkan
pengakuan dari masyarakat maka berkembang lagi menjadi warga yang harus
menjalankan fungsi dan perannya sehingga tercipta kehidupan bertetangga yang
rukun.
PERTEMUAN 20
2)
Lembaga agama
Lembaga agama adalah sistem
keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan
dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial
pada masyarakat. Agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur
kehidupan rohani manusia.
Kehidupan beragama didukung oleh
kegiatan peribadahan. Ibadah yang dilakukan didasari keyakinan masing-masing.
Berikut ini adalah gambar tempat peribadah yang ada di Indonesia:
=============
<<وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم
مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ((108
=============
Secara jelasnya, fungsi lembaga
keagamaan antara lain sebagai berikut:
a)
Sebagai pedoman hidup bagi
manusia, baik dalam kehidupan pribadi dengan tuhannya, baik dengan sesama
manusia maupun terhadap alam sekitar.
b)
Sumber kebenaran.
c)
Tuntunan prinsip benar dan salah.
d)
Pedoman keyakinan berbuat baik
e)
Pedoman keberadaan yang
hakikatnya adalah ciptaan Tuhan semata.
f)
Pedoman dalam mencari kepuasan
hakiki, baik dhohir maupun bathin.
3)
Lembaga ekonomi
Lembaga ekonomi adalah bagian
dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan
kebutuhan sehari-hari.
Fungsi lembaga ekonomi antara
lain adalah sebagai berikut:
a)
Memberikan pedoman untuk
mendapatkan bahan pangan.
b)
Memberikan pedoman untuk
melakukan pertukaran barang atau barter.
c)
Memberikan pedoman tentang harga
jual beli barang.
d)
Memberikan pedoman untuk
menggunakan tenaga kerja.
e)
Memberikan pedoman tentang cara
pengupahan.
f)
Memberikan pedoman tentang cara
pemutusan hubungan kerja.
g)
Memberi identitas bagi
masyarakat.
PERTEMUAN 21
4)
Lembaga pendidikan
Lembaga pendidikan adalah lembaga
atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk
mengubah tingkah laku individu kepada kehidupan yang lebih baik melalui
interaksi dengan lingkungan sekitar.
Fungsi manifest lembaga
pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:
a)
Mempersiapkan anggota masyarakat
untuk mencari nafkah.
b)
Mengembangkan bakat perseorangan
demi kepuasan pribadi maupuan bagi kepentingan masyarakat
c)
Melestarikan kebudayaan
masyarakat.
d)
Menanamkan keterampilan yang
perlu bagi pastisipasi dan demokrasi.
Fungsi laten lembaga pendidikan
antara lain adalah sebagai berikut:
a)
Mengurangi pengendalian orang
tua.
b)
Mempertahankan/memperbaiki sistem
kelas sosial.
c)
Memperpanjang masa remaja.
5)
Lembaga politik
Pengertian
Secara etimotogis, politik
berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara.
Kemudian arti berkembang menajdi polities yang berarti warga negara. Politeia
yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Politika yang berarti
pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Kata ‘politisi’
berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
Politik adalah proses pembentukan
dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses
pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Definisi lain dari politik adalah
usaya yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Lembaga politik merupakan suatu
lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan
masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan
bermasyarakat.
Macam-macam Lembaga Politik
Lembaga-lembaga politik yang
berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut:
a)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
b)
Presiden dan Wakil Presiden
c)
Dewan Perwakilan Rakyat
d)
Dewan perwakilan Daerah
e)
Pemerintah Daerah
f)
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
g)
Partai Politik
Fungsi Lembaga Politik
Secara fundamental, lembaga
politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam
masyarakat.
Fungsi lembaga politik dapat
diuraikan sebagai berikut:
a)
Memelihara ketertiban dalam
negeri
Cara yang dilakukan bisa
persuasif (penyuluhan) maupun koersif (kekerasan/ketegasan).
b)
Mengusahakan kesejahteraan umum
Daftar pustaka










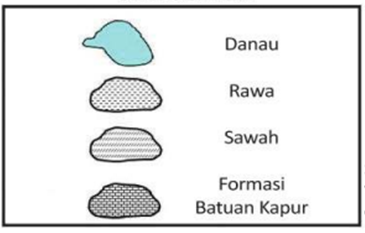

















0 komentar:
Posting Komentar